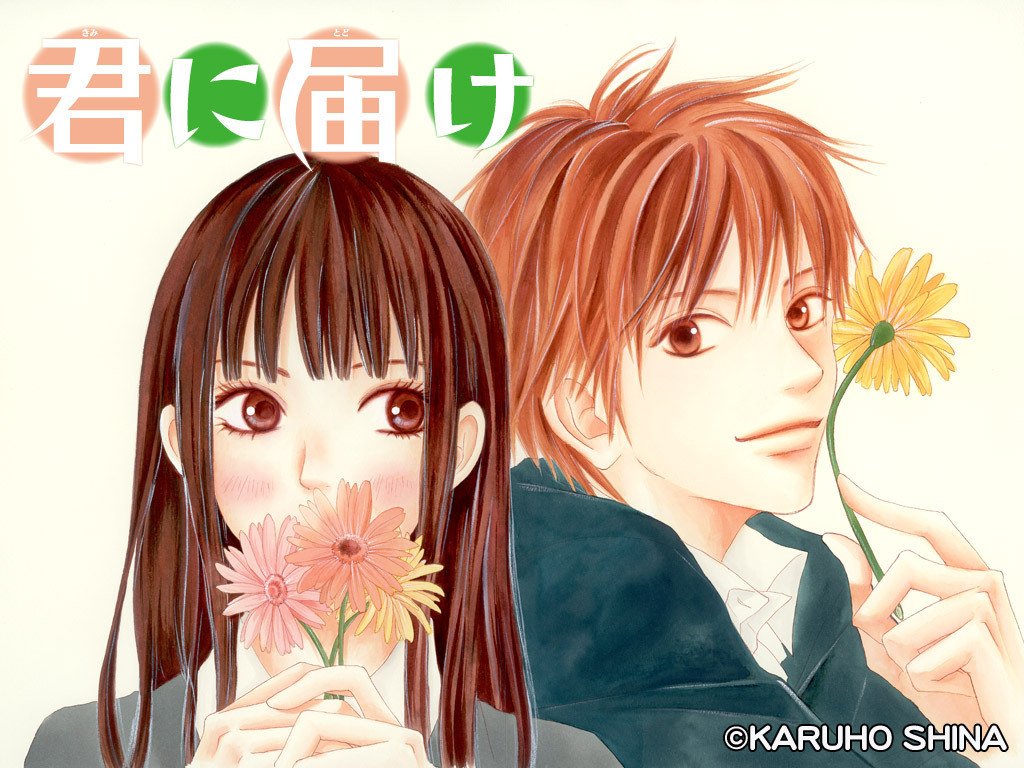❤ Good Morning ◕‿◕ Afternoon ❤ Evening ღ Night ◕‿◕
Mereka Tidak Tahu
by : M.Yoshepine
Kuakui Athalone memang kota yang indah. Nyaris sempurna, begitulah. Sayang
selalu ada noda yang mengotori setiap kesucian. Tak terkecuali kemurnian kota
ini, cemar oleh cela yang tak sedikit. Dan aku sadar betul, aku bagian dari
bercak itu. Flek hina yang mencoreng wajah Athalone.
Nathaniel, biasa dipanggil Nathan oleh orang-orang di sekitarnya. Tebakanku
tepat saat menerka umur anak ini. Tujuh belas tahun empat bulan, duduk di
bangku sekolah menengah, dan sedang giat-giatnya menimba ilmu. Dia tidak bodoh,
cukup cerdas untuk bocah seumurnya. Entah apa yang membuat ia menanamkan bagian
jiwanya padaku ketika itu.
Sesampainya ia di rumah, dilihatnya seorang gadis berambut ikal pendek
sedang tertawa gembira sambil berputar-putar mengenakan gaun putih yang belum sempurna
seutuhnya. “Lizbeth, coba Mama lihat sebentar. Sepertinya ada bagian yang
terlalu besar. Mama tandai dulu, Sayang.”
”Iya, Ma,” jawab Lizbeth ringan, kemudian mendekatkan diri pada ibunya.
Nathan menyipitkan mata ke arah mereka, mengirimkan gelombang kebencian
pada keduanya. Anak berpakaian pesta itu kemudian menemukan manik matanya dan
tersenyum lebar. “Kak Nathan, tidak biasanya pulang cepat?” ucapnya lembut,
masih dengan wajah sumringah.
Sorot mata Nathan dingin menatap perempuan yang tak lain adalah adiknya
itu, teguran barusan tidak digubrisnya sama sekali. Aku tak tahu pasti apa yang
Nathan inginkan, namun aku yakin pikiran jahat tengah berputar dalam benaknya
saat ini. Ia menggerakkan pandangan matanya ke punggung sang ibunda, menatap
dalam dan tak juga ia lepaskan.
Tiba-tiba wanita yang tengah membenahi bagian cacat pada gaun itu
menusukkan jarum ke tubuh Lizbeth. Mustahil seorang ibu demikian ceroboh
apalagi sengaja melakukannya. Pasti Nathan yang membuat tangan perempuan itu
bergerak di luar kendali. Luka yang ditimbulkan oleh jarum itu tampaknya cukup dalam,
sebab tak mungkin gadis itu begitu cengeng sampai refleks melompat dan
berkaca-kaca hanya karena tertusuk jarum kecil di permukaan kulitnya.
“Ma, sakit…,” rengek Lizbeth. Ada setitik merah pada pinggangnya. Darah.
“Ya Tuhan! Maafkan Mama, Lizbeth. Mama tidak sengaja,” seru wanita itu
panik. Cepat-cepat ia membungkuk, mencoba melepas jarum dari pakaian itu.
Perlahan namun pasti Nathan mengangkat kedua ujung bibirnya, berjalan
menjauhi mereka. Kini aku sadar mengapa ia rela menukar apapun untuk kekuatan
itu. Ia tidak memerlukan harta, takhta, atau apapun. Ia hanya butuh aku demi
memenangkan perhatian orang tuanya.
Baru beberapa menit Nathan memejamkan mata seraya berbaring di atas
tempat tidur, bunyi ketukan di pintu kamarnya memaksa ia membuka kelopak mata.
“Kak, main yuk!” kata suara di balik pintu, masih mengetuki papan kayu tebal
yang membatasi ruang antara mereka. Lizbeth.
“Malas!” jawab Nathan kasar dari dalam kamar.
“Ayolah, aku mohon. Aku kesepian,” rajuk adiknya lagi, berusaha mengusir
rasa malas sang kakak yang sesungguhnya hanya sebatas ucapan.
“Peduli setan! Main dengan Mama saja!” bentaknya dengan nada tinggi.
“Mama pergi ke pasar, Kak….” Nada bicara Lizbeth terdengar memelas.
Pergi? Ini kesempatan emas, bisiknya perlahan di dalam batin.
Kemudian ia bangkit berdiri dari pembaringannya dan berjalan ke arah pintu.
“Mau main apa?” tanyanya datar.
Mereka hanya bermain lempar tangkap bola di sebidang lahan kosong dekat
rumah. Sama sekali tidak menyenangkan, menurutku. Nathan menganggap ini
membosankan, namun Lizbeth tak henti-hentinya tertawa, seakan ini memang
permainan favoritnya.
Muak dengan bibir Lizbeth yang terus menerus mencerminkan kebahagiaan,
Nathan mengedikkan kepalanya dan membuat bola tenis bertuliskan inisial nama
Lizbeth yang dilempar ke arahnya berbelok dan memecahkan kaca jendela rumah
seorang tetangga.
“Yah… tamat.” Nathan merendahkan nada suaranya. Masalah. Itu yang sejak
tadi ia tunggu.
“Gawat. Bagaimana ini, Kak?” tanya gadis itu panik.
“Kau ambil sendiri. Aku mau belajar.” Besok hari Sabtu. Sebuah kobohongan
besar bila ia mengatakan hendak menelaah isi buku pelajaran.
Lizbeth mulai menangis, mengemis belas kasihan kakaknya. Nathan memandang
adiknya dengan tatapan jijik kemudian melangkah pergi, membiarkannya tenggelam
dalam isak sendirian. Tak sedikitpun hatinya tergerak untuk menolong Lizbeth. Agaknya
kegelapan telah melebur dengan batinnya, memangkas nurani sedikit demi sedikit.
Seperti yang telah kuduga, Nathan tidak benar-benar meninggalkan Lizbeth.
Malahan ia mengikuti secara diam-diam ke mana adiknya itu pergi. Mustahil
Lizbeth memilih pulang. Tak ada yang dapat diharapkannya. Kemungkinan besar ia akan mencari bantuan lain karena sang
kakak tidak peduli padanya. Ia berjalan perlahan ke sebuah pohon besar, menemui
seorang anak laki-laki yang tengah melamun di bawah rindangnya tanaman itu.
“Ada apa, Lizbeth? Mengapa menangis?” tanya si lelaki yang parasnya sedikit
lebih tua dari Lizbeth, memecah lamunannya sendiri.
“Tidak. Hanya ada sedikit masalah,” jawab Lizbeth lesu. Kemudian ia
meletakkan tubuhnya di sebelah laki-laki muda itu.
“Katakan saja. Mungkin aku bisa bantu.” Dari intonasi perhatiannya aku bisa
tahu mereka berteman baik. Persahabatan mereka terlihat tulus. Terlalu tulus
untuk sebuah hubungan pria dan wanita.
“Richard… sebenarnya aku… tidak sengaja memecahkan kaca jendela rumah Pak
Gilbert,” ucap Lizbeth terbata-bata. “Aku takut.”
Setelahnya Lizbeth menceritakan kisah itu dari awal. Bagaimana ia dan
kakaknya bermain dengan penuh suka cita, bagaimana bola itu secara ajaib
berbelok dan membuat masalah, bagaimana Nathan menolak untuk menolongnya, serta
perasaan takut yang berkecamuk dalam hatinya.
Richard tersenyum sesaat lalu menghapus air mata yang menggenang di pelupuk
mata Lizbeth. Sontak Nathan yang sedari tadi menyaksikan pembicaraan mereka
mengepalkan tangannya dan menggeram penuh amarah.
Nathan terus mengamati mereka. Hanya dengan sebuah tatapan benci, salah
satu dahan pohon yang berada tepat di atas kepala sang adik sengaja
dipatahkannya. Lizbeth bisa saja terbunuh bila Richard tidak mendorong dan
menyelamatkannya dari maut. Sekali lagi, Nathan mengeraskan rahang, menatap
lelaki di samping adiknya dengan mimik keji.
“Terima kasih,” kata Lizbeth dengan kelopak mata terbuka lebar, masih tak
percaya nyawanya hampir melayang. Untuk beberapa detik mereka saling bertatapan
bak putri raja yang baru diselamatkan pangerannya dari naga api.
Napas Richard terdengar berat, mewarnai keheningan yang tercipta di antara
mereka. “Ya… sama-sama,” balasnya datar. “Aku sangat takut tadi.”
“Aku juga,” ucap Lizbeth sambil mengelus dada. Senyum mulai merekah di
wajahnya. Ia tertawa kecil, kemudian berkata, “Kamu cocok jadi pahlawan.
Pembela kebenaran yang melindungi kota ini. Pasti keren!”
Bibir Richard beku, tak mampu menyuarakan apapun.
Kau pikir siapa dirimu? Jangan halangi aku bila kau
tak ingin kehilangan seluruh hidupmu, desis Nathan pada dirinya sendiri.
“Jadi… bagaimana bola itu? Mau kuambilkan?” tanya sang pangeran kepada tuan
putri. Mata pangeran itu berbinar, menjanjikan mentari dalam gulita wanitanya.
“Jangan! Pak Gilbert orang yang kejam. Aku tidak mau kamu terluka,” jawab
Lizbeth cepat. “Besok aku ambil sendiri. Aku bilang pada orang tuaku dulu nanti
malam.”
***
Segera setelah Lizbeth pergi, Richard bangkit dan berjalan ke arah lapangan
kosong itu. Ia tidak menghiraukan peringatan Lizbeth sama sekali. Hari mulai
gelap, jingga menguasai cakrawala, melengserkan takhta sang biru. Perlahan
Richard mengetuk pintu rumah yang jendelanya berlubang dan masuk saat sang
pemilik mempersilahkannya. Nathan mengikutinya, mencoba mendengar isi
percakapan mereka.
“Benar ini milikmu? Di bola ini tertulis huruf E, bukankah namamu Richard?”
tanya seorang dewasa yang aku yakin bernama Gilbert.
“E… Evander. Itu nama tengahku.” Hanya dengan mendengar nada bicara tanpa
melihat ekspresinya pun aku tahu ia berbohong. E untuk Elizabeth, tentu saja.
Terdengar bunyi telapak tangan yang memukul sesuatu diikuti dengan hujatan
kata-kata kasar. Entah apa yang mereka lakukan di dalam sana. Kemudian sebuah
bola melompat keluar dari lubang di kaca yang sama dengan tempatnya masuk
beberapa jam lalu, mendarat dan menghilang dalam barisan ilalang tinggi di
pinggir lahan.
Gilbert yang disebut Lizbeth kejam ternyata lebih jahanam dari yang
kubayangkan. Ia menyeret Richard menuju rumahnya, menerobos langit kelam yang
disinari cahaya redup. Berniat meminta uang ganti rugi, kurasa. Nathan melihat
semua itu dalam seringai yang tak terdefinisikan jahatnya.
Cukup lama Nathan mencari bola di antara semak lapangan hijau yang kini
berubah kelabu di bawah naungan malam. Mungkin terlalu lama sampai ketika ia
telah menemukan apa yang ia cari dan hendak menghanguskannya, suara seorang
laki-laki terdengar dari balik punggung.
Richard. Siapa lagi?
“Jadi kamu sudah menemukannya?” Seketika Nathan berbalik dan mendapati lelaki itu
berdiri tegak sekitar lima meter di hadapannya. Ujung bibir Richard berdarah,
mungkin Gilbert menamparnya. “Tolong kembalikan bola itu pada Lizbeth. Katakan
saja Pak Gilbert yang memberikannya padamu.”
“Cukup. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang lebih menggelikan
darimu. Kau ingin sok pahlawan? Atau sok malaikat pelindung?” tanya Nathan
dengan nada tinggi.
“Bukan begitu, aku hanya––”
Belum sempat Richard menyelesaikan kalimatnya, Nathan menyela, “Berikan
sendiri padanya!” Ia melempar bola yang sejak tadi digenggamnya tepat ke tengah
dada Richard. Lajunya terlalu kencang hingga Richard tak mampu menangkapnya dan
membiarkan dirinya jatuh ke tanah akibat hantaman benda itu.
“Kamu bukan Nathan yang aku kenal,” katanya sambil meringis, menahan sakit
yang pasti merajai seluruh tubuh. Ia terduduk di rerumputan, menatap wajah
Nathan dengan pandangan aneh.
Nathan kembali tersenyum dan meninggalkan Richard bersama perihnya di
tengah gelap malam. Semenjak kejadian itu Nathan sering mempergunakanku untuk
mencelakai Lizbeth. Semakin hari semakin jahat. Namun, ada atau tidak ada
Richard, Lizbeth selalu lolos dari bahaya yang ia ciptakan. Dan itu membuat
kebencian Nathan pada adiknya kian bertumpuk.
Aku tidak mengerti bagaimana Nathan bisa kehilangan jiwa persaudarannya
dengan Lizbeth. Adiknya itu tidak pernah berbuat iseng atau kurang ajar, ia
menyayangi kakaknya dan aku yakin itu. Hari ini Nathan berniat untuk
menyelesaikan semuanya. Segala yang telah ia mulai sejak terikat denganku.
“Kakakmu itu aneh,” ujar Richard di bawah pohon yang sama dengan waktu itu.
Lizbeth duduk di sampingnya, mendengar tiap kata yang ia lafalkan, namun tetap
memilih diam.
Mendengar kalimat itu, Nathan yang sejak beberapa menit lalu memang sedang
mencari Lizbeth mempercepat langkahnya. Richard memandangnya heran dan
menggenggam tangan Lizbeth kuat-kuat ketika Nathan berdiri tepat di depan wajah
mereka berdua.
“Ikut aku,” ucap Nathan seraya menarik bahu Lizbeth, memaksanya berdiri.
Tanpa diperintahkan Richard pun turut berdiri. Nathan yang mulai membenci
Richard karena terlalu sering ikut campur menepis bahu pemuda itu dan
membuatnya terhempas ke tanah, seolah gravitasi bumi menariknya demikian kuat.
“Richard!” jerit Lizbeth.
“Selanjutnya giliranmu,” bisik Nathan di telinga Lizbeth. Refleks Richard
menahan kaki kiri Nathan agar tak dapat bergerak.
“Pergi dari sini, Lizbeth.” Napas Richard berkejaran dengan kalimatnya
barusan. Nathan lalu mendorong Lizbeth, melumpuhkannya sebelum langkah pertama.
Lizbeth hanya bisa beringsut mundur, tak kuasa berdiri. Gurat wajahnya
mengumandangkan ketakutan yang luar biasa.
“Lepaskan aku!” bentak Nathan pada Richard. Sementara itu, Lizbeth terus
menjauhkan diri dari kakaknya, berusaha menyelamatkan hidupnya yang terancam.
Nathan menghentikan waktu. Membuat seluruh kota kecuali dirinya dan dua
orang di dekatnya beku pada sebuah posisi. Angin berhenti bertiup dan dedaunan
yang diterbangkannya melayang di udara, seakan segan jatuh ke bumi.
“Apa yang terjadi padamu?” balas Richard dengan suara bergetar. Ekspresi
wajahnya takjub sekaligus marah. Nathan mendelik tajam tepat pada korneanya dan
tiba-tiba saja Richard melepaskan tangannya dari kaki Nathan bagaikan tersengat
arus listrik.
Richard benar saat menyebut Nathan yang ada di hadapannya bukanlah Nathan
yang ia kenal dahulu. Mungkin sebaiknya aku ceritakan pertemuan Nathan dengan
wanita itu. Juga perjanjian yang mengubah seluruh hidupnya.
#####
Sudah lebih dari satu dekade aku mengabdi pada Quella, perempuan licik yang
aku yakin tidak sendirian menghitamkan kota ini. Selama itu pula sudah puluhan
bahkan mungkin ratusan nyawa kami kumpulkan. Ia kumpulkan, sebenarnya. Aku tidak pernah
mendapatkan apapun. Hanya sedikit orang yang mengenalnya. Begitu lebih baik
sebab aku tak ingin ia menghancurkan Athalone semakin jauh.
Quella bukanlah ahli sihir atau sejenisnya. Ia hanya manusia biasa yang
memanfaatkan kelalaian manusia lainnya sebagai pemuas hidup. Aku pun demikian.
Hanya alat yang ia pergunakan untuk mencapai ambisi gelapnya: menaklukkan
Athalone, mengubah tiap jengkal kota ini sebagai taman bermainnya.
“Apa yang bisa kuperbuat untukmu?” tanya Quella pada seorang laki-laki waktu itu. Aku
mengetahui nama lelaki itu setelah enam jam bersamanya. Nathaniel Prestoner.
Ia tidak menjawab. Aku bisa melihat putus asa mengelilingi atmosfernya.
Memang seperti itulah raut setiap orang yang datang pada Quella. Manusia-manusia
yang hampir hilang tujuan hidupnya.
“Aku butuh… kekuatan,” jawab si anak pelan. Jawaban semacam itu sudah
berkali-kali kudengar. Kekuatan, kejayaan, kekayaan, kehormatan, kenikmatan…
permintaan mereka takkan jauh dari hal-hal duniawi. “Berapa harganya?”
“Separuh nyawamu,” kata Quella santai. Sejak dulu itulah bayarannya. Tak
pernah lebih, tak pernah kurang.
“Apa? Maksudmu umurku akan lebih pendek dari yang seharusnya?” ucap lelaki
itu. Nadanya terdengar panik, seolah maut sedang mengejarnya. Tidak tahukah ia
bahwa tak ada seorangpun termasuk dirinya sendiri yang mampu meramalkan usia
seseorang?
“Separuh nyawamu, bukan separuh usiamu. Percayalah padaku, tidak akan ada
bedanya.” Itulah kalimat andalan Quella. Belum pernah ada penolakan setelah kata-kata
manis itu terucap.
“Baiklah. Bagaimana aku memberinya?”
Kemudian Quella tersenyum tipis ke arah remaja laki-laki itu. Tidak, ia
tidak cantik saat tersenyum. Sama sekali tidak. Ruangan sempit yang lebih mirip
tempat praktek penganut ilmu hitam itu bahkan menambah kengerian di wajahnya.
“Berikan tanganmu,” lafalnya lembut.
#####
Nathan membalikkan tubuhnya. “Kenapa sulit sekali memusnahkanmu?” Nada
bicara Nathan keras saat mengatakan itu, ditujukannya bagi Lizbeth. “Kali ini
aku pastikan kau mati. Di bawah kakiku!”
Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Lizbeth, ia tak kuasa mengucapkan
sepatah katapun. Nathan berjalan cepat ke arahnya. Aku tidak tahu dengan cara
apa ia akan membunuh adiknya. Yang jelas dominasiku dalam dirinya telah
membutakan nurani dan mata hati hingga ia tega berbuat sekeji itu. Hebatnya semua
ini hanya berawal dari setitik dengki.
“Nathan!” Richard berteriak keras, berusaha menghentikan langkah kaki
Nathan yang terus mendekati Lizbeth. Aku tak menyangka tubuhnya yang lemah
masih sanggup berdiri. Ia bahkan hampir menyentuh pundak Nathan kalau saja tak
tersentak kuat saat lelaki itu membalikkan tubuhnya. Seakan disibak angin
puting beliung, Richard terlempar begitu jauh ke belakang. Punggungnya menabrak
batang pohon yang menjadi saksi bisu perhelatan mereka. Pasti sangat
menyakitkan. Lizbeth sampai memejamkan matanya dengan cepat saat itu terjadi,
tak sanggup menyaksikan perih yang menjalari tubuh Richard.
Dari riak muka Richard aku tahu tubuhnya hampir remuk. Kenyataan itu
memaksa Lizbeth untuk berhenti bergerak, meluangkan waktu yang sebenarnya tidak
berjalan. Ia hanya takut tak memiliki detik lain untuk memastikan keselamatan
jiwa Richard. Itu yang membuatnya bergeming.
Belum puas Nathan melihat Richard kesakitan, tangannya terapung ke udara,
kemudian mencengkeram kehampaan di hadapannya. Tanpa disentuh Richard mengerang
nyaring, meronta-ronta di bawah tumbuhan itu seolah tubuhnya sedang dikuliti.
“Berhenti, berhenti!” jerit Lizbeth di dalam isak. Air mata meleleh di
pipinya, berjatuhan membasahi tanah.
Nathan tertawa mendengar mereka. Erangan kesakitan, jeritan ketakutan…
mungkin baginya perpaduan semua itu lebih indah dari alunan musik manapun.
Setelah ia puas menyiksa Richard, tubuhnya kembali menghadap pada adiknya. Air
mata gadis itu telah mengering, namun raut ketakutan di wajahnya belum surut.
Perlahan ia mendekatkan dirinya pada Lizbeth. Pelan sekali, seakan
memainkan emosi sang adik. Lizbeth masih mencoba melangkah mundur walaupun ia
tahu itu sia-sia.
“Liz… beth…,” desah Richard pelan. Nyawaku pasti sudah tak ada lagi dalam
raga bila jadi dirinya. Sungguh mengesankan melihatnya berusaha mati-matian
melindungi Lizbeth.
“Selamat tinggal adik kecil.” Kini Nathan hanya berjarak satu meter di
depan Lizbeth. Ia mengangkat tangannya ke udara, bersiap mendengar dentingan
merdu lainnya. Lizbeth melihat ke arah lain dan kelopak matanya ia paksa
menutup. Hanya rasa takut teramat sangat yang tersisa di wajahnya.
Baru saja Nathan akan menggerakan jarinya dan mengulang apa yang ia lakukan
pada Richard, tubuhnya hilang keseimbangan dan jatuh berdebum mencium kaki
Lizbeth. Nyawanya habis. Akhirnya.
Nathan menyerahkan separuh nyawanya pada Quella, namun tak diberi tahu
tentang ini. Tentang kemungkinan yang terjadi bila terlalu sering
mempergunakanku. Memang inilah tujuan Quella dari awal: memiliki seluruh nyawanya
secara utuh, bukan hanya sebagian.
“Kakak!” Lizbeth yang merasa kakinya tersentuh lembut langsung membuka mata
dan panik setengah mati mendapati kakaknya tergeletak hampir lenyap.
“Aku bukan kakakmu…,” ucap Nathan lirih dengan sisa tenaganya, memandang
iris mata Lizbeth yang kehijauan. “Apa kau tidak tahu aku hanya anak adopsi?”
Lizbeth diam seribu bahasa.
“Kau lahir setahun setelah aku diadopsi. Karena itulah Papa dan Mama lebih
menyayangimu.” Nathan kemudian tertawa kecil, merasa bodoh di hadapan adik
perempuannya. Adik yang hampir saja ia bunuh.
“Kakak salah. Kakak salah!” seru Lizbeth. Air matanya yang tadi telah
mengering kembali berjatuhan. “Mereka menyayangi Kakak… sama seperti aku. Nama
Kakak sama dengan nama Papa, kan? Itu bukti cinta mereka.”
“Omong kosong….” Nathan tersenyum kecut. Mimiknya tampak mendung, seolah
menyesal telah memilihku sebagai tujuan hidupnya.
“Apa Papa dan Mama pernah menyakiti Kakak? Aku tak pernah melihat mereka
melakukan itu.” Lizbeth tak henti-hentinya berucap, mengajak Nathan bicara,
menunda kepergian kakaknya itu.
“Tidak. Memang tidak. Aku hanya iri padamu. Aku iri karena kau memiliki
orang tua sedangkan aku tidak.”
“Bicara apa Kakak? Papa dan Mama orang tua kita!” Nada bicara Lizbeth yang
biasanya lembut kini berubah keras.
Nathan memejamkan matanya sesaat kemudian membukanya kembali dan berkata,
“Semenjak pertama kali aku diadopsi oleh mereka… Kakek dan Nenek tak pernah
menganggapku ada. Semakin parah saat kau lahir. Keluarga besar menyayangimu, tetapi tidak mengakui
aku sebagai kakakmu. Kau tahu seberapa sakitnya itu?” Intonasinya melemah,
mengisyaratkan kematian yang kian mendekat.
Air semakin deras menghiliri pipi Lizbeth. Ia membenamkan wajahnya pada
dada Nathan dan mendekapnya kuat, membuat air mata merembes mengenai permukaan
kulit sang kakak. “Aku… minta maaf,” gumamnya tak jelas di tengah isak. Percuma
saja, Lizbeth. Kakakmu akan segera musnah dari dunia ini. Seluruhnya, bukan
hanya raganya.
“Su… dahlah… Lizbeth….” Lirih bercampur pedih terdengar jelas dalam
intonasi kalimat barusan. Richard yang mengucapkannya.
“Maafkan aku. Aku gelap mata. Jaga Lizbeth baik-baik, Richard.” Itu kalimat
terakhir yang keluar dari bibirnya. Segera setelah nyawanya benar-benar habis,
waktu kembali berjalan. Daun-daun kering yang sempat tertunda kepulangannya
dengan gembira membelai bumi. Tubuh Nathan lenyap bak pasir tertiup angin,
bersamaan dengan menghilangnya segala kenangan dan ingatan tentang dia. Punah
dari memori setiap manusia yang pernah mengenalnya. Nathaniel Prestoner tidak
pernah ada.
***
Quella berjalan mantap ke arahku, memungutku dari tanah dengan ekspresi
puas yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Satu lagi nyawa yang ia dapatkan.
“Kerja bagus, Kalcaros.” Ia tersenyum kemudian memasukkan tubuhku ke dalam
kantung jaketnya. Sampai detik ini aku tidak tahu apa tujuannya mengumpulkan
nyawa-nyawa itu. Bisa jadi ada hubungannya dengan ambisi untuk menguasai
Athalone, atau mungkin tidak. Hanya satu yang aku tahu pasti: perbuatan jahat
mengurangi nyawa manusia.
Mungkin sebenarnya bukan aku yang melahap habis seluruh nyawa mereka.
Perasaan dan emosi manusia yang senantiasa teraduk-aduk dan tak pernah stabil
itulah yang menjatuhkan mereka ke dalam jurang kesesatan. Rasa haus yang takkan
pernah bisa terpuaskan atau dendam yang tiada berujung mungkin jauh lebih
berbahaya dari dominasiku dalam jiwa mereka. Satu perbuatan buruk akan menarik
pada perbuatan-perbuatan buruk berikutnya. Semakin lama semakin busuk, layaknya
Nathan yang kehilangan kasih dan berniat membunuh adiknya.
Sudahlah, manusia memang begitu. Baik Quella si pengumpul nyawa maupun
Nathan si pendengki, keduanya hanya melakukan apa yang menurut mereka benar dan
apa yang mereka inginkan. Bukan apa yang sebenarnya baik dan benar.
Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. [ ]